 Oleh Mhd Darwinsyah Purba
Oleh Mhd Darwinsyah Purba
Maraknya sastra religius belakangan ini memang menggembirakan. Hanya saja, ada sebuah tantangan besar yang perlu dipikirkan terkait dengan mutu atau kualitas sastra religius itu. Sebab, bagaimanapun sastra itu bermain dalam wilayah estetika.
Perkembangan sastra religius memang marak akhir-akhir ini. Hanya saja, ada yang perlu dipikirkan terkait dengan kualitas estetika dan pemahaman pada masalah religiusitasnya. Mengapa demikian? Dalam konteks sastra religius, pandangan umum menangkap bahwa yang dinamakan sastra religius adalah sastra atau karya sastra yang mengusung lambang-lambang agama, baik itu Islam, Kristen dan lainnya. Dengan begitu, penyebutan beberapa metafor dalam karya itu mengacu pada kekhasan dari sebuah agama. Tak heran bila posisi sastra religius selalu mengacu pada agama formal. Hanya saja, konsepsi umum itu mendaptkan penyangkalan yang cukup signifikan dari beberapa teks sastra yang memiliki kandungan religiusitas tinggi.
Salah satunya dari Jalaludin Rumi, seorang sufi dan penyair Persia terkemuka. Salah satu puisinya yang dikenal dalam hal ini adalah:
Jangan tanya apa agamaku
bukan Yahudi
bukan Zoroaster
bukan pula Islam
Karena aku tahu
begitu suatu nama kusebut
begitu Anda memberikan arti yang lain
Daripada makna yang hidup di hatiku
Abu Mansur Al Hallaj (tokoh sufi dikenal dengan ungkapan ektasenya: Anal Haq), juga pernah menulis gagasannya tentang religiusitas dan agama: Aku telah renungkan agama-agama, yang membuatku berusaha keras untuk memahaminya. Dan aku baru sadar bahwa agama-agama itu, kaidah-kaidah unik, dengan sejumlah cabang.
Di sisi lain yang bermain dalam konteks agama-agama formal adalah yang terkait dengan dogma, sehingga kungkungan adanya konsep realisme dogmatis atau idealis dogmatis begitu mewarnai konstruksi dan penyebutan sastra religius itu. Dalam satu sisi, hal ini hampir sama dengan konsep realisme sosial yang digagas dalam sastra-sastra marxis, terlebih komunis.
Poisisi ini tidak akan menemukan titik tertingginya, jika acuannya memang benar-benar sangat formalis, karena selama ini religiusitas dipahami sebagai sebuah kualitas keagamaan. Dalam satu sisi religiusitas berbeda dengan sitem religi. Religiusitas tidak hanya berkutat pada masalah ketuhanan yang digariskan agama formal. Religiusitas lebih mengarah pada kesadaran ketuhanan yang termanifestasikan dalam nilai-nilai dan asas kemanusiaan.
Jadi posisinya tidak hanya transeden dalam arti teologi, tetapi juga imanen. Dalam kerangka Islam, tendensi yang diemban bukan hanya hubungan dengan Tuhan (hablum minallah), tetapi juga fungsi sosialnya, hubungan dengan sesamanya (hablum minan nas). Jadi posisi manusia juga diperhatikan, dan yang menjadi acuan adalah faktor kemanusiaan yang luas, yang menjadi landasan dari sebuah bangunan keagamaan. Dengan demikian, bangunan estetis yang terkonstruksi dalam sastra religius tidak mengacu pada dogma yang bermain dalam tataran hukum positivisme atau syariah.
Dalam masalah keindahan, Sayyed Husein Nasr mengungkap bahwa dalam keindahan itu terdapat pengetahuan tertinggi dan kesucian, sehingga seni-seni tradisional yang meliputi jiwa murni seharusnya memang dikembangkan, sebab posisi kemanusiaan benar-benar terpelihara. Di sini, posisi agama tidak lagi beban dalam upaya mengejawantahkan ekspresi dalam wilayah estetika dan proses kreatif.
Kondisi ini akan berlaku, jika pemahaman agama tidak terkungkung dalam sebuah bangunan struktur yang merujuk pada penafsiran tunggal. Dalil-dalil yang mengacu pada pemahaman yang dangkal pada kebebasan dan pembebasan ekspresi dalam seni memang harus ditafsir-ulangkan. Pembacaan tidak lagi bersifat heuristik, tetapi hermeneutik, dengan mengacu tiadanya prasangka dan proses penafsiran atau pembacaan itu merupakan bagian dari sejarah itu sendiri, seperti ide hermeneutika yang pernah digagas Gadamer.
Dengan landasan kemanusiaan, pembacaan terhadap realitas keagamaan itu bisa pula menggunakan strategi dekonstruksi Derrida, dengan paradigma bahwa sebuah teks itu tidak utuh. Ia memiliki celah dan jarak pemaknaan. Bisa pula dengan discourse Foucault dengan melihat asal pengetahuan dan konteks terjadinya teks. Umpamanya, jika agama formal melarang menvisualkan manusia, maka posisi seni tidak lagi terlarang menvisualkan manusia, dengan mempertimbangkan kembali bahwa manusia tidak lagi manifestasi dari ‘Tuhan’. Ada jarak pemaknaan dan rentang waktu dan bergesernya penafsiran. Di sisi lain, religiusitas dikembalikan pada posisi asali, tidak lagi apriori pada ‘the other’ atau manusia lain di luar keyakinan sendiri.
Hal itu karena dengan merujuk pada sifat Islam yang rahmatan lil ‘alamin, yang tidak lagi memberikan previliese dengan mengedepankan binary oposotion dalam pemihakan kebenaran atau memberi keistimewaan pada pihak-pihak tertentu, maka konsepsi religiusitas itu tidak hanya membentur dinding konsep status quo. Sebab, ambiguitas pada realitas bisa memberikan nilai tambah bahwa seni, sastra dan budaya bisa menelusup dalam bayang Tuhan dalam memahami realitas kemanusiaan. Ia, seni dan sastra religius, bisa jadi tidak sekedar pengejawantahan nilai-nilai agama. Religiusitas menjelma ruh atau nyawa dari konstruksi kebudayaan yang mengusung humanisme.
Mungkin yang perlu dikedepankan di sini, bahwa proses penciptaan karya-karya religius tidak harus terjebak pada dogma agama. Ia bersifat bebas dan merupakan proses pembebasan juga. Bisa menggunakan lambang-lambang agama formal sebagai bahan, hanya saja ada pertanggung jawaban estetik. Dalam hal ini, bisa berupa sebagai pengangkatan pada celah dan sisi yang perlu diperbaiki dari agama itu, yang mungkin lebih menekankan pada aturan-aturan rutinitas dan tidak sampai pada penghayatan yang menyusup hingga tulang sumsum, dengan sentral masih berkutat dan berpihak pada sisi kemanusiaannya.
Erich From dalam To Have or To Be pernah menegaskan, religiustitas merupakan ornamen dari watak sosial yang harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan religius yang sudah melekat pada diri manusia, sebagai kebutuhan asasi. Ia mesti tidak berkaitan dengan sistem yang berhubungan dengan Tuhan atau berhala, melainkan pada sistem pemikiran atau tindakan yang memberikan pada individu suatu kerangka oroentasi dan suatu objek kebaktian. Hal ini mengacu pula pada konsep agama yang membebaskan yang digagas Fromm dalam Religion dan Psychoanalysis. Seperti juga yang ditulis Nietzsche dalam Also Sprach Zarathustra: “Aku butuh Tuhan yang mengerti bagaimana menari”.
Dalam sastra Indonesia modern, sastra religius yang paling baik masih dipegang oleh cerpen AA Navis dalam Robohnya Surau Kami. Dalam cerpen yang kental dengan tradisi Minang yang memang ketat dalam masalah agama, cerpen itu sepenuhnya mengusung nilai-nilai religiusitas yang tidak mempermasalahkan aspek religius dalam penyebutan Tuhan dalam agama formal, tetapi lebih menekankan pada faktor manusianya, dengan jalan menggugah keberadaan manusia itu sendiri dalam sistem religi yang berkembang di sana. Bahkan, dalam satu sisi, cerpen ini mempertanyakan nilai terdalam dari sistem religi itu, dengan memunculkan nilai-nilai religiustitas yang perlu ditumbuhkembangkan. Bahkan, ‘surau’ bisa pula dianggap sebagai penanda dari sebuah kebobrokan sistem yang hanya mengedepankan sebuah tatanan formal dan mapan dari sebuah agama.
skip to main |
skip to sidebar
Popular Posts
-
Tan Kamelo: Mendiknas tidak tegas! MHD DARWINSYAH PURBA WASPADA ONLINE MEDAN - Pakar hukum Prof. DR. Tan Kamelo, SH, MS menegaskan, jika Dir...
-
341 konsumen tertangkap basah mencuri listrik MHD DARWINSYAH PURBA WASPADA ONLINE MEDAN - Realisasi operasi P2TL sadar wilayah Sumut yang d...
-
Komisi E DPRDSU tidak tahu apa-apa MHD DARWINSYAH PURBA WASPADA ONLINE MEDAN - Kemelut Dualisme Yayasan UISU terus menjadi agenda besar bai...
-
Kamar hotel sekelas melati MHD DARWINSYAH PURBA WASPADA ONLINE MEDAN - Sejumlah anggota jemaah haji ONH plus asal Sumatera Utara yang dibera...
-
YUSRIZAL, MHD DARWINSYAH PURBA & LINDA Y HASIBUAN WASPADA ONLINE MEDAN - Secara matematis, di atas kertas bandara baru di Kualanamu dipa...
-
Waspada! cuaca ekstrim di perairan Nias MHD DARWINSYAH PURBA WASPADA ONLINE MEDAN - Sejak Shubuh hujan rintik-rintik membasahi kota Medan sa...
-
MHD DARWINSYAH PURBA WASPADA ONLINE MEDAN - Gubsu Syamsul Arifin harus menindak tegas Pj Bupati Batubara terkait gagalnya pelaksanaan ujian ...
-
*MPR akan pertanyakan ke Menteri Agama MHD DARWINSYAH PURBA & IBRAHIM JALIL WASPADA ONLINE MEDAN - Beragam komentar para jemaah haji asa...
-
MHD DARWINSYAH PURBA WASPADA ONLINE MEDAN - Banyaknya traffic light atau lampu merah yang mati tentu membuat lalu lintas macet. Bahkan ada y...
-
MHD DARWINSYAH PURBA WASPADA ONLINE MEDAN - Pekerja di Indonesia merupakan suatu polemik yang tiada habisnya untuk dibicarakan oleh masyarak...
Daftar Blog Saya
Diberdayakan oleh Blogger.
Pengikut
Arsip Blog
-
▼
2008
(143)
-
▼
November
(78)
-
▼
Nov 09
(13)
- Peranan Politik Mahasiswa dalam Pilkada
- Cerpen pujangga
- Hamzah al-Fansuri Sang Penyair dan sufi agung
- Cerpen pujangga
- Karya Sastra dalam Membangun Moralitas Bangsa
- Cerpen pujangga
- Sastra Religiustitas yang Berkualitas
- Perempuan, Sumber Inspirasi penciptaan seni
- Cerpen pujangga
- Cerpen Pujangga
- Cerpen pujangga
- Cerpen Pujangga
- Cerpen Pujangga
-
▼
Nov 09
(13)
-
▼
November
(78)
Labels
- l (1)
Blog Archive
-
▼
2008
(143)
-
▼
November
(78)
-
▼
Nov 09
(13)
- Cerpen Pujangga
- Cerpen Pujangga
- Cerpen pujangga
- Cerpen Pujangga
- Cerpen pujangga
- Perempuan, Sumber Inspirasi penciptaan seni
- Sastra Religiustitas yang Berkualitas
- Cerpen pujangga
- Karya Sastra dalam Membangun Moralitas Bangsa
- Cerpen pujangga
- Hamzah al-Fansuri Sang Penyair dan sufi agung
- Cerpen pujangga
- Peranan Politik Mahasiswa dalam Pilkada
-
▼
Nov 09
(13)
-
▼
November
(78)










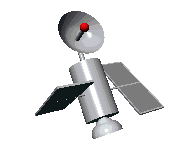

0 comments:
Posting Komentar